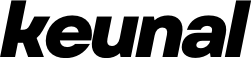Berita mengejutkan dari Bandung Barat menyebar cepat, menjadi pembicaraan di mana-mana: lebih dari 1.300 anak sekolah menjadi korban keracunan massal setelah menyantap menu dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Peristiwa yang terjadi pada akhir September 2025 ini bukanlah insiden tunggal, melainkan puncak dari masalah yang telah lama membayangi program ambisius pemerintah. Tragedi ini memicu kesadaran pahit bahwa kasus serupa ternyata sudah banyak terjadi di seluruh negeri, memaksa publik untuk bertanya: program ini harus dievaluasi total atau gagal total?
Krisis di Bandung Barat terungkap secara bertahap, menunjukkan eskalasi kegagalan sistem yang mengerikan. Semuanya dimulai pada hari Senin, 22 September 2025, ketika gelombang pertama keracunan menghantam. Sebanyak 411 anak dari klaster dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Cijambu tumbang setelah menyantap menu MBG. Seharusnya, ini menjadi alarm paling keras bagi seluruh pemangku kepentingan untuk menghentikan sementara seluruh operasional di wilayah tersebut.
Keesokan harinya, Selasa, 23 September 2025, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat memang merespons dengan menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB). Namun, deklarasi ini ternyata hanyalah respons birokratis di atas kertas. Saat status KLB diumumkan, dapur-dapur lain, termasuk SPPG Neglasari, tetap diizinkan beroperasi. Akibatnya bisa ditebak: bencana yang lebih besar pun meledak. Pada hari Rabu, 24 September 2025, dua klaster baru muncul secara bersamaan. Sebanyak 730 anak menjadi korban dari klaster SPPG Neglasari, dan 192 siswa lainnya dari klaster SPPG Mekarmukti di Cihampelas.
Total korban pun meroket melampaui angka 1.333 siswa, tersebar di Kecamatan Cipongkor dan Cihampelas. Pusat kesehatan masyarakat dan GOR Cipongkor disulap menjadi ruang perawatan massal, namun tetap tak mampu menampung semua korban. Para korban mengalami gejala keracunan yang parah: mual-mual, sesak napas, pusing, lemas, hingga kejang-kejang. Sebagian yang mengalami dehidrasi berat dan penurunan kesadaran harus dilarikan ke RSUD Cililin, yang dengan cepat mencapai kapasitas maksimalnya.
Biang keladinya diduga kuat adalah makanan yang sudah basi. Kesaksian para siswa menyebutkan menu seperti daging ayam, nasi, dan tahu yang mereka terima sudah berbau asam dan warnanya aneh. Fakta bahwa pemerintah daerah tidak menginstruksikan penghentian operasional seluruh dapur setelah KLB ditetapkan adalah sebuah kelalaian yang tak termaafkan, sebuah kegagalan komando dan kontrol yang berujung pada penderitaan ribuan anak.
Pola Bencana yang Terus Berulang
Seiring meluasnya berita dari Bandung Barat, kesadaran publik pun terbuka. Ternyata, kasus keracunan akibat program MBG sudah ada sebelumnya juga. Sebuah sinyal bahwa apa yang terlihat di permukaan hanyalah sebagian kecil dari masalah yang jauh lebih besar dan sistemik.
Program yang digadang-gadang sebagai investasi untuk masa depan bangsa ini justru menjelma menjadi ancaman kesehatan berskala nasional. Jauh sebelum 1.333 siswa di Bandung Barat menjadi korban, rentetan kasus serupa telah terjadi di berbagai penjuru negeri. Jawa Barat, ironisnya, menjadi episentrum dari krisis ini, dengan laporan kasus keracunan massal sebelumnya di Garut, Tasikmalaya, Sukabumi, dan Cianjur.
Namun, masalah ini tidak terbatas di satu provinsi. Wabah keracunan akibat program MBG telah menyebar ke seluruh nusantara. Di Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, 29 murid SD dilarikan ke puskesmas, Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, 27 siswa mengalami nasib serupa. sedangkan di Mamuju, Sulawesi Barat, 23 siswa menjadi korban, yang berujung pada penutupan dapur MBG setempat. Bahkan di Ketapang, Kalimantan Barat, 25 orang keracunan setelah menyantap menu MBG yang, secara mengejutkan dan tidak masuk akal, menyajikan ikan hiu goreng.
Akar Masalah: Dari Dapur Hingga Istana
Rentetan tragedi ini memunculkan satu pertanyaan mendasar: mengapa program dengan niat baik bisa berakhir menjadi bencana yang terus berulang? Menurut pengamat kebijakan publik, Dr. Trubus Rahardiansyah, pemerintah terjebak dalam fokus untuk meningkatkan kuantitas atau jumlah dapur SPPG, sambil mengabaikan kualitas dan standar keamanan pangan. Ambisi untuk menggelar program secara masif dan cepat telah mengorbankan aspek paling krusial: keselamatan anak-anak.
Kegagalan paling nyata terjadi pada rantai pasok dan manajemen dapur. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyoroti praktik manajemen penyajian yang buruk. Ia memberikan contoh: makanan dimasak pada pukul 1 dini hari untuk kemudian didistribusikan pada pukul 12 siang. Jeda waktu 11 jam ini adalah surga bagi pertumbuhan bakteri, mengubah makanan bergizi menjadi racun. Masalah ini diperparah oleh kurangnya keahlian. Banyak juru masak di dapur SPPG yang tidak memiliki pelatihan atau sertifikasi memadai dalam hal higienitas pangan.
Di atas kegagalan operasional, terdapat lapisan masalah yang lebih dalam: lemahnya pengawasan dari Badan Gizi Nasional (BGN). Para pengamat menyoroti kontrol BGN yang sangat lemah terhadap yayasan-yayasan yang ditunjuk sebagai mitra. Tidak ada kejelasan apakah yayasan-yayasan ini benar-benar memiliki kapasitas atau hanya bertindak sebagai perantara. Sikap “tunggu arahan” dari pimpinan BGN, yang menyatakan masih menunggu instruksi dari Presiden, menunjukkan betapa lamban dan tidak responsifnya birokrasi dalam menghadapi krisis yang menyangkut nyawa anak-anak.
Semua kegagalan teknis ini berakar pada benturan antara ambisi politik dan realitas operasional. Program MBG adalah proyek mercusuar dan janji kampanye utama. Ada tekanan politik yang luar biasa untuk menggulirkannya secepat mungkin. Akibatnya, standar kualitas, keamanan, dan pengawasan dikorbankan demi mengejar target kuantitas. Ribuan kasus keracunan ini bukanlah “kecelakaan”, melainkan konsekuensi yang dapat diprediksi dari implementasi program yang terburu-buru.
Suara Publik dan Pertaruhan Kepercayaan
Di tengah keresahan ini, keluhan masyarakat melampaui sekadar data statistik. Keluhan mereka adalah potret kegagalan program di tingkat paling dasar: makanan yang tidak enak, menu yang tidak sesuai dengan budaya lokal, hingga yang paling fatal, makanan basi yang menyebabkan keracunan. Program yang seharusnya memberikan manfaat justru secara aktif mendatangkan mudarat.
Setelah melihat semua masalah ini, dari kegagalan sistemik hingga penderitaan individu, satu pertanyaan besar menggantung di benak kita semua: sebaiknya harus diapakan program ini?
Desakan paling kuat datang dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan JPPI, yang menuntut pemerintah memberlakukan moratorium atau menghentikan sementara seluruh program MBG secara nasional. Argumen mereka sederhana: sebuah program yang secara aktif membahayakan anak-anak tidak boleh dilanjutkan satu hari pun. Namun, sebagian anggota DPR berpendapat bahwa solusi yang tepat adalah evaluasi dan perbaikan, bukan penghentian.
Apapun keputusan yang diambil, melanjutkan program dalam bentuknya saat ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai tanggung jawab. Kepercayaan publik telah mencapai titik kritis. Visi besar di balik program MBG—untuk menciptakan lapangan kerja dan membangun Generasi Emas 2045—kini berhadapan dengan realitas pahit anak-anak yang dirawat di fasilitas kesehatan.
Hal ini membawa kita kembali pada pertanyaan yang paling mendasar, sebuah pertanyaan sinis namun sangat relevan yang lahir dari kekacauan dan ketidakjelasan program ini.
Jadi, MBG itu sebenarnya singkatan dari apa sih? Tuangkan pendapat Anda di kolom komentar!