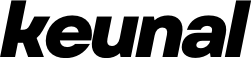Keunal – Di tengah kemajuan teknologi dan kemudahan akses informasi pada tahun 2025, masyarakat justru menghadapi tantangan baru dalam mencapai kesejahteraan mental. Meskipun berbagai fasilitas hidup semakin modern, data menunjukkan bahwa tingkat kepuasan hidup tidak serta-merta meningkat berbanding lurus dengan kemudahan tersebut. Pertanyaan mendasar kembali muncul di tengah masyarakat: jika konsep bahagia itu sederhana, mengapa realitasnya sering kali terasa rumit untuk dicapai?
Fenomena ini menjadi relevan seiring dengan meningkatnya laporan mengenai tekanan psikologis, khususnya pada kelompok usia produktif. Kerumitan dalam meraih kebahagiaan saat ini dinilai bukan disebabkan oleh kurangnya sumber daya, melainkan oleh persepsi dan standar sosial yang terus berubah akibat paparan digital yang intensif.
Psikologi di Balik Banyaknya Pilihan
Salah satu faktor utama yang membuat kebahagiaan terasa sulit dicapai adalah fenomena psikologis yang dikenal sebagai “Paradoks Pilihan”. Dalam teori yang dikemukakan oleh Barry Schwartz, ketersediaan opsi yang terlalu banyak—mulai dari pilihan karier, produk gaya hidup, hingga hiburan—justru membebani proses pengambilan keputusan seseorang.
Alih-alih merasa bebas, individu sering kali merasa cemas salah memilih. Hal ini memicu ketidakpuasan kronis karena seseorang cenderung membandingkan pilihan yang diambil dengan opsi lain yang ditinggalkan. Dalam konteks tahun 2025, di mana algoritma digital menyajikan pilihan tanpa batas setiap saat, standar kepuasan menjadi tidak stabil dan terus meningkat, membuat rasa “cukup” semakin sulit diraih.
Tekanan Standar Sosial dan Data Kesehatan Mental
Kerumitan ini tercermin dalam data kesehatan mental terbaru. Laporan dari Naluri mengenai kondisi kesehatan mental di kawasan Asia periode 2024-2025 menyoroti bahwa Generasi Z merupakan kelompok yang paling rentan mengalami kecemasan. Salah satu pemicu utamanya adalah tekanan untuk memenuhi ekspektasi sosial yang tinggi.
Sebuah riset yang dipublikasikan dalam Jurnal Kesehatan Tambusai pada pertengahan 2025 mengonfirmasi korelasi antara penggunaan media sosial dan tingkat ketidakbahagiaan. Paparan terus-menerus terhadap kurasi kehidupan orang lain menciptakan standar kompetitif. Kebahagiaan tidak lagi diukur dari ketenangan personal, melainkan dari pencapaian yang dapat dipamerkan secara visual. Hal ini mengubah definisi bahagia dari kondisi internal menjadi validasi eksternal.
Pergeseran Makna Kebahagiaan
Kompleksitas juga muncul karena masyarakat modern cenderung mengaitkan kebahagiaan dengan kepemilikan materi yang berlebihan. Padahal, studi terbaru yang dikutip oleh CNBC Indonesia pada Agustus 2025 menegaskan bahwa faktor utama kebahagiaan jangka panjang adalah kualitas hubungan sosial dan kesehatan fisik, bukan akumulasi harta benda.
Penelitian tersebut menyoroti bahwa aktivitas sederhana seperti interaksi bermakna dengan komunitas, waktu istirahat yang cukup, dan rasa syukur memiliki dampak yang lebih signifikan terhadap stabilitas emosi. Namun, hal-hal mendasar ini sering kali terabaikan karena masyarakat sibuk mengejar target-target yang dianggap sebagai simbol kesuksesan modern.
Mengembalikan Kesederhanaan
Melihat tren yang berkembang menjelang tahun 2026, tantangan terbesar bagi masyarakat adalah menyederhanakan kembali pola pikir. Bahagia menjadi rumit karena adanya penambahan syarat-syarat eksternal yang sebenarnya tidak esensial. Kunci untuk mengurai kerumitan ini terletak pada kemampuan individu untuk membatasi paparan informasi yang tidak perlu dan fokus pada prioritas hidup yang nyata.
Kebahagiaan sejatinya tetap sederhana: kondisi di mana kebutuhan fisik dan emosional terpenuhi dengan seimbang. Upaya untuk mengurangi komparasi sosial dan menetapkan standar pribadi yang realistis diprediksi akan menjadi langkah krusial bagi masyarakat untuk mendapatkan kembali kualitas hidup yang sehat secara mental.